Opini
Program Sertifikasi Tanah Gratis: Menata Ulang Akses dan Keadilan Tanah Ulayat di Sumatera Barat?
Sertifikasi tanah ulayat seharusnya difasilitasi dalam bentuk kolektif dan tidak bisa dijadikan sarana privatisasi atas nama legalitas.
Oleh: Lina Hasyyanti Gulo, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas
"Sertifikasi tanah ulayat seharusnya difasilitasi dalam bentuk kolektif dan tidak bisa dijadikan sarana privatisasi atas nama legalitas. Keadilan agraria harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial, bukan sekadar efisiensi administratif."
Pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir terus meningkatkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang populer dengan istilah “sertifikasi tanah gratis”. Program ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk mewujudkan keadilan agraria dan kepastian hukum atas tanah, sebagaimana tertuang dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Tujuan dari program ini secara normatif adalah positif: memberikan legalitas terhadap hak atas tanah bagi masyarakat secara masif, mempercepat proses legalisasi aset, dan mendukung inklusi keuangan.
Ketika program ini diterapkan di daerah dengan karakteristik hukum adat yang kuat seperti Sumatera Barat yang masih mempertahankan sistem tanah ulayat sebagai wujud warisan kearifan lokal Minangkabau muncul berbagai persoalan kritis. Salah satunya: apakah program sertifikasi tanah gratis ini sejalan dengan semangat perlindungan tanah ulayat dan keadilan kelompok dalam masyarakat adat?
Dalam sistem adat Minangkabau, tanah ulayat adalah sumber utama kehidupan, kehormatan, dan identitas kaum. Hak atas tanah tidak dimiliki secara individual, melainkan kolektif oleh suatu kaum (kelompok kekerabatan matrilineal) yang dikepalai oleh ninik mamak. Tiga jenis tanah ulayat dikenal dalam masyarakat Minang: ulayat suku, ulayat kaum, dan ulayat nagari. Setiap jenis ulayat memiliki fungsi sosial tersendiri dan tidak bisa dialihkan tanpa musyawarah adat.
UUPA Tahun 1960 telah mengakui keberadaan hak ulayat melalui Pasal 3 yang menyatakan: "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Akan tetapi, pengakuan ini masih bersifat deklaratif dan sering kali tidak memiliki daya ikat administratif tidak seperti sertifikat hak milik (SHM) atau hak guna usaha (HGU).
Dalam kerangka hukum nasional, sertifikasi tanah melalui program PTSL umumnya diberikan dalam bentuk hak individual seperti SHM. Mekanisme ini bertentangan dengan konsep komunal hak ulayat yang tidak mengenal kepemilikan pribadi. Akibatnya, dalam pelaksanaan PTSL di Sumatera Barat, tanah ulayat berpotensi diklaim sebagai milik perseorangan tanpa melalui musyawarah adat, terutama bila pengakuan formal atas status ulayat belum dilakukan.
Baca juga: Selesaikan Sengketa Lahan Ulayat Sikabau, DPRD Pasaman Barat Resmi Bentuk Pansus
Laporan lapangan dari berbagai LSM dan akademisi menunjukkan bahwa ada tren individualisasi kepemilikan tanah ulayat, terutama oleh generasi muda Minang yang semakin akrab dengan logika hukum negara ketimbang hukum adat. Misalnya, seseorang dapat mengklaim sebidang tanah ulayat yang telah digarap turun-temurun oleh keluarganya dan mendaftarkannya atas nama pribadi melalui PTSL, tanpa izin dari kaum atau ninik mamak. Ketika sertifikat SHM sudah terbit, kedudukan hukum adat menjadi sangat lemah untuk melakukan gugatan atau penolakan.
Hal ini sejalan dengan kritik Paul Scholten bahwa hukum tertulis cenderung “membatu” dan tidak cukup adaptif terhadap norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Maka, hukum negara dalam bentuk sertifikat pertanahan dapat justru menjadi instrumen legalisasi perampasan tanah ulayat yang selama ini dilindungi oleh hukum adat.
Pada konteks pengelolaan sumber daya alam, tanah ulayat seringkali menjadi sasaran empuk investasi. Ketika tanah belum bersertifikat, negara melalui skema HGU bisa menyerahkannya kepada korporasi, dengan dalih sebagai tanah negara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya (khususnya PP No. 18 Tahun 2021), proses pelepasan tanah adat bisa dilakukan apabila tidak memiliki pengakuan administratif. Inilah bentuk eksklusi struktural masyarakat adat dari akses terhadap haknya sendiri, karena mereka terjebak dalam sistem hukum negara yang tidak memfasilitasi pengakuan hak komunal secara memadai.
Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, disebutkan bahwa “hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola berdasarkan hukum adat yang berlaku.” Putusan ini semestinya menjadi basis konstitusional untuk memperkuat pengakuan atas tanah dan wilayah adat, termasuk tanah ulayat. Akan tetapi, dalam praktik, mekanisme administrasi pertanahan belum sepenuhnya responsif terhadap semangat putusan tersebut.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka ruang bagi rekognisi desa adat. Dalam Pasal 103 disebutkan bahwa desa adat dapat mengelola hak asal usulnya, termasuk penguasaan atas tanah ulayat. Jika lembaga adat diakui secara formal sebagai wujud dari hukum publik, maka mereka berhak menjadi subjek hukum dalam proses sertifikasi tanah secara kolektif. Model ini lebih adil dan akomodatif bagi masyarakat adat yang selama ini tersingkir dari sistem administrasi pertanahan negara.
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Sertifikat Tanah Ulayat di Sumbar Masih Jauh dari Target, Baru 10 Bidang
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 juga menyediakan skema penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat. Namun, kebijakan ini belum berjalan efektif, karena syarat administratifnya dianggap terlalu berat dan prosesnya panjang. Dibutuhkan political will dari pemerintah daerah untuk menginisiasi pengakuan hukum adat secara kolektif, dan bukan sekadar menyerahkan beban pembuktian kepada masyarakat adat yang sering kali tidak memiliki akses terhadap dukungan teknis dan hukum.
Boedi Harsono dalam Hukum Agraria Indonesia (2007) menyebut bahwa pengakuan hak ulayat harus memenuhi tiga kriteria: (1) ada komunitas hukum adat; (2) ada sistem norma adat yang masih hidup; dan (3) ada wilayah tertentu yang menjadi tempat berlakunya hukum adat tersebut. Di Sumatera Barat, ketiga syarat ini masih terpenuhi, sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan keberadaan hak ulayat.
Dalam hal ini, program sertifikasi tanah gratis tidak boleh dijalankan secara seragam. Diperlukan kebijakan afirmatif untuk wilayah adat. Sertifikasi tanah ulayat seharusnya difasilitasi dalam bentuk kolektif dan tidak bisa dijadikan sarana privatisasi atas nama legalitas. Keadilan agraria harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial, bukan sekadar efisiensi administratif.
Pertama, perlu ada revisi terhadap skema PTSL agar bisa mengakomodasi sertifikasi kolektif bagi tanah ulayat dan tanah adat. Kedua, lembaga adat harus diberdayakan sebagai mitra resmi dalam proses pendaftaran tanah, baik dalam verifikasi data historis maupun dalam mediasi konflik. Ketiga, pemerintah daerah harus aktif memfasilitasi pengakuan hukum atas masyarakat hukum adat, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Keempat, pendidikan hukum dan sosial kepada generasi muda adat sangat penting agar nilai kolektif tanah ulayat tidak terkikis oleh logika hukum individualistik.
Tanah ulayat bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol identitas, kepercayaan, dan kesinambungan sosial masyarakat Minangkabau. Sertifikasi tanah gratis hanya akan menjadi instrumen keadilan apabila dirancang dengan kepekaan terhadap konteks lokal dan norma adat yang hidup. Program ini harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat masyarakat adat, bukan melemahkannya. Di sinilah letak tantangan negara modern: bagaimana mengakui tanpa menundukkan, dan bagaimana melayani tanpa merusak.(*)
Program Sertifikasi Tanah Gratis
Tanah Ulayat
Sumatera Barat
Lina Hasyyanti Gulo
ilmu hukum
Universitas Andalas
| Ibu dan Sumber Kehidupan dalam Dialog Getir |

|
|---|
| Jika Tidak Bertemu dengan Nan Ampek, Celaka lah yang Gadaikan dan Jual Harta Pusako di Minangkabau |

|
|---|
| Islam dan Disabilitas: Keteladanan Nabi, Hak Setara untuk Semua |

|
|---|
| Citra Masakan Padang Terjun Bebas: Antara Gengsi dan Perang Harga Murah! |
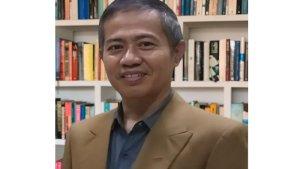
|
|---|
| Menikam Jejak dan Mengembalikan Kejayaan Kopi di Nagari Pagadih |

|
|---|

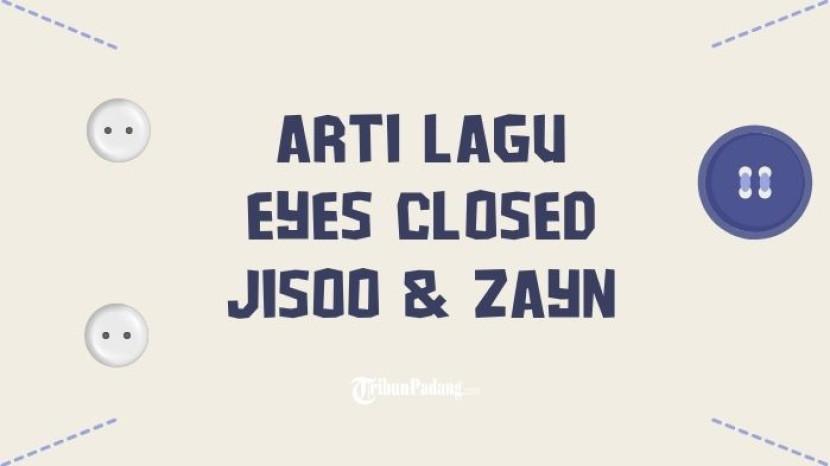













Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.