Citizen Journalism
Opini: Pembangunan Jalan Tol Sumatera Barat: Antara Kepentingan Umum dan Hak Atas Tanah
SEIRING perkembangan zaman, dunia berkembang pesat di antaranya dalam perkembangan bidang infrastruktur. Inovasi pembangunan infrastruktur, khususnya
Oleh : Salsabila Azzura, S.H. Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Andalas
SEIRING perkembangan zaman, dunia berkembang pesat di antaranya dalam perkembangan bidang infrastruktur. Inovasi pembangunan infrastruktur, khususnya jalan merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah di Indonesia.
Ternyata, pembangunan jalan tol pertama di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978 yaitu Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi).
Lebih tepatnya, tanggal 9 Maret 1978 Presiden Soeharto meresmikan jalan tol ini dengan panjang 59 kilometer/KM. Berbeda dengan daerah lain yang sudah ada jalan tol sejak lama, pembangunan jalan tol di Sumatera Barat baru di bangun mulai Tahun 2018.
Pembangunan jalan tol di Sumatera Barat menjadi topik yang sangat layak untuk diperbincangkan saat ini. Beberapa tahun terakhir pemerintah Sumatera barat semakin gencar membangun infrastruktur jalan tol.
Tujuannya utamanya yaitu untuk meningkatkan konektifitas antarwilayah dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Khususnya jalan tol Padang-Pekanbaru menjadi proyek strategis nasional yang digadang-gadang akan mendongkrak perekonomian daerah.
Namun, di tengah pembangunan tersebut, muncul sebuah dilema krusial: bagaimana menyeimbangkan kepentingan umum dengan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat, terutama tanah ulayat yang menjadi ciri khas sistem agraria Minangkabau?
Terjadinya konflik antara proyek pembangunan dan hak atas tanah bukanlah fenomena baru. Di banyak daerah di Sumatera Barat, proses pembebasan lahan sering kali diwarnai protes warga, sengketa hukum, hingga penolakan dari ninik mamak yang merasa tanah pusaka kaum mereka dirampas secara sepihak.
Masalah ini menjadi semakin kompleks karena menyinggung dua ranah sekaligus: hukum negara dan hukum adat.
Secara normatif, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk membebaskan lahan demi pembangunan infrastruktur.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memberi ruang bagi negara untuk menggunakan tanah demi pembangunan.
Baca juga: Prodi Magister Manajemen Bencana UNAND & Tim AusAid Program SIAP SIAGA Australia, Perkuat Kerjasama
Selama dilakukan dengan prosedur yang benar, transparan, dan dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada pemilik atau penguasa tanah. Namun, implementasi di lapangan sering kali jauh dari ideal.
Dalam konteks hukum agraria, persoalan ini sangat kompleks karena menyangkut hak konstitusional warga negara atas tanah dan pemanfaatan ruang.
Dasar utama pengaturan tanah di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa "seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia adalah milik negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Namun penting untuk dicatat, penguasaan negara atas tanah bukan bersifat absolut, melainkan mengandung kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat hukum adat.
Lalu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Namun demikian, pelaksanaan pembangunan atas nama "kepentingan umum" harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak warga, terutama mereka yang terdampak langsung.
Dalam konteks Sumatera Barat, banyak persoalan muncul karena sebagian besar tanah yang terkena proyek pembangunan adalah tanah ulayat tanah adat yang tidak didaftarkan secara formal ke negara, tetapi memiliki kekuatan hukum dan legitimasi sosial yang tinggi dalam struktur adat Minangkabau.
Sejauh ini, tanah ulayat tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh kaum atau suku, dan pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab ninik mamak.
Oleh karena itu, proses pengadaan tanah atas tanah ulayat seharusnya melibatkan musyawarah secara menyeluruh dengan seluruh pemangku adat, bukan hanya kepada perorangan atau perwakilan pemerintah nagari.
Baca juga: Selesaikan Sengketa Lahan Ulayat Sikabau, DPRD Pasaman Barat Resmi Bentuk Pansus
Persoalan berikutnya terletak pada ganti rugi. Banyak masyarakat adat merasa bahwa nilai ganti rugi yang diberikan negara tidak setara dengan nilai sejarah, sosial, dan ekonomi tanah mereka.
Apalagi tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan keberlanjutan sosial sebuah kaum. Ketika tanah ulayat digusur, maka hilang pula satu bagian penting dari struktur sosial masyarakat adat.
Ketidakhadiran negara dalam menjamin keterlibatan aktif masyarakat adat bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah dan identitas budaya.
Laporan Komnas HAM pun beberapa kali mencatat adanya pelanggaran hak masyarakat adat dalam proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) atau persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan secara memadai.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Sumatera Barat dan kabupaten/kota, harus mengambil peran aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap proses pengadaan tanah.
Pemerintah tidak cukup hanya menjadi perpanjangan tangan dari proyek nasional, tetapi juga harus menjadi pelindung nilai-nilai lokal yang menjadi kekayaan Sumatera Barat.
Diperlukan juga adanya kebijakan daerah yang lebih afirmatif dalam melindungi tanah ulayat. Pemerintah bisa menyusun Perda tentang perlindungan tanah ulayat dan mekanisme partisipatif dalam pengadaan tanah.
Selain itu, perlu dibentuk lembaga mediasi agraria yang melibatkan unsur pemerintah, adat, dan masyarakat sipil untuk menyelesaikan konflik tanah secara damai dan adil.
Pembangunan tidak boleh hanya dimaknai secara fisik semata. Jalan tol yang megah tidak akan berarti jika di atasnya berdiri kekecewaan masyarakat yang merasa haknya diabaikan.
Negara harus mengubah paradigma pembangunan dari "pembangunan untuk rakyat" menjadi "pembangunan bersama rakyat". Proyek pembangunan tidak boleh lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan menjadi ruang partisipasi, dialog, dan keadilan.
Penting juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah.
Masyarakat harus tahu bahwa mereka berhak menolak jika tidak ada kesepakatan, berhak atas kompensasi yang layak, dan berhak atas informasi yang transparan. Negara yang adil adalah negara yang hadir untuk semua, bukan hanya untuk investor dan pemegang proyek.
Pembangunan jalan di Sumatera Barat pada hakikatnya adalah langkah strategis yang harus didukung semua pihak. Namun keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa panjang jalan yang berhasil dibangun, melainkan dari seberapa adil prosesnya dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Kepentingan umum bukan berarti mengorbankan hak-hak rakyat, melainkan mengakomodasi seluruh kepentingan dengan prinsip keadilan dan musyawarah. Negara harus memastikan bahwa pembangunan jalan tidak menjadi jalan sunyi bagi keadilan sosial.
Jalan itu harus menghubungkan bukan hanya antarwilayah, tetapi juga antara negara dan rakyatnya dengan ikatan kepercayaan, penghormatan, dan kesetaraan hak.(*)
| MAN IC Padang Pariaman Menebar Harapan Jemput Masa Depan: Berakit-rakit ke Hulu, Berenang ke Tepian |

|
|---|
| Kuliah Kerja Nyata: Program Mahasiswa di Indonesia Serupa, Bakti Siswa & Magang Industri di Malaysia |

|
|---|
| Opini Ruang Kota Tanpa Asap: Car Free Day Antara Negara Serumpun Indonesia & Malaysia |

|
|---|
| Opini Bahasa Melayu: Bila Percuma di Malaysia, Gratis di Indonesia |

|
|---|
| UNP Pelatihan Emotional Spritual Question di SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Sumatera Barat |

|
|---|

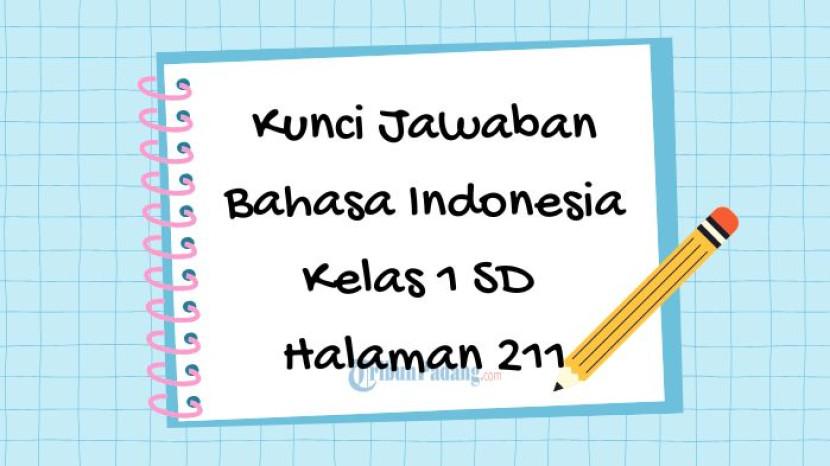








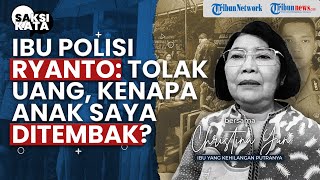





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.