OPINI
Memperbaiki UU Bermasalah
Memperbaiki UU Bermasalah, Oleh Helmi Chandra SY, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta & Peneliti Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI)
Oleh: Helmi Chandra SY
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta & Peneliti Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI)
Presiden Jokowi akhirnya menandatangani UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di tengah kritik keras dari kelompok pekerja atau buruh, akademisi serta mahasiswa. Keadaan ini semakin menambah panjang daftar produk legislasi yang bermasalah, setelah sebelumnya perubahan UU KPK, UU Minerba dan UU MK juga menuai penolakan publik.
Alasan paling mendasar dari penolakan UU Cipta Kerja disebabkan pembentukannya oleh DPR dan pemerintah dianggap tidak transparan serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup. Selain itu, proses kilat dalam pembentukan UU Cipta Kerja semakin memperburuk hasil akhir dari UU yang diharapkan akan menambah lapangan pekerjaan tersebut.
Buruknya hasil UU Cipta Kerja terlihat dari kesalahan-kesalahan mendasar pada naskah resmi UU yang telah diundangkan pemerintah dalam lembaran negara. Kesalahan itu, antara lain ditemukan pada Pasal 6 di Bab III yang berbunyi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a. Namun jika dicermati, Pasal 5 Ayat (1) yang dirujuk tersebut ternyata tidak ada dalam UU Cipta Kerja. Kesalahan rujukan juga tertera pada Pasal 175 di Bab XI, dimana Pasal 53 Ayat (5) merujuk ke Ayat (3) padahal mestinya yang dirujuk adalah Ayat (4) karena Ayat (3) tidak ada hubungannya sama sekali.
Melihat preseden buruk legislasi ini tentu timbul pertanyaan krusial tentang bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan teks UU setelah diundangkan. Menurut penulis perbaikan terhadap UU yang telah disahkan bahkan diundangkan dalam lembaran negara haruslah dengan cara konstitusional, dimana setidaknya hanya ada 3 (tiga) cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk itu.
Pertama, melakukan revisi UU, perbaikan terhadap kesalahan suatu UU baik makna maupun teks lazim dilakukan dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara menyisipkan atau menambah materi ke dalam rumusan UU serta dapat juga dilakukan dengan maksud menghapus dan mengganti sebagian materi UU yang direvisi. Ketentuan perubahan ini merujuk pada lampiran UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi dasar bagi DPR maupun pemerintah untuk membentuk setiap produk hukum.
Ketatnya prosedur perubahan sebuah UU tentu punya maksud dan tujuan untuk menjaga kesakralan dan wibawa sebuah UU. Sebuah UU yang telah diundangkan dalam lembaran negara sesungguhnya sudah melawati 2 (dua) tahap pengesahan yakni pengesahan materiil yang dilakukan DPR dalam rapat paripurna terakhir bersama pemerintah serta pengesahan formil oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Untuk itulah, melakukan perbaikan dengan mengabaikan ketentuan tersebut sama dengan menghilangkan wibawa UU sekaligus marwah DPR dan Presiden dalam waktu bersamaan.
Kedua, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), secara konstitusional, Perppu merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu termaktub dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden berhak menetapkan perppu. Perppu tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya, dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Ketentuan seperti itu sejatinya menjadi “senjata” bagi pemerintah dalam hal ini Presiden untuk dapat mengoreksi UU bermasalah yang dibuat bersama DPR.
Keputusan Presiden menerbitkan Perppu juga menjadi jalan keluar terhadap kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Ditambah Perpu dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan prosedur biasa pembentukan UU bersama DPR karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Hal ini tentu sangat sejalan dengan tafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga mempertegas melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa dalam pembentukan sebuah Perppu.
Perppu juga menjadi bukti tanggung jawab moral pemerintah yang menjadi inisiator pengusul UU Cipta Kerja. Kesalahan dalam naskah UU baik yang bersifat clerical error dengan alasan salah pengetikan maupun kesalahan yang dapat merubah makna tentu tidak dapat ditoleransi.
UU yang dibentuk tidak hanya mengikat pemerintah sebagai pembentuk tetapi juga akan mengikat masyarakat secara luas. Sehingga sebagai pertanggungjawaban moral seharusnya Presiden langsung merespon tanpa mengulur-ulur waktu dengan mengeluarkan Perppu karena Pasal 186 UU Cipta Kerja menyebut bahwa UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ketiga, melakukan pengujian di MK, sejatinya ada 2 (dua) jenis pengujian yang dapat dilakukan di MK yakni pengujian materil dan pengujian formil. Pengujian secara formil secara singkat disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (3) huruf a, UU No 24 tahun 2003 tentang MK yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan sebuah UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.
Pengujian secara formal akan dilakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan UU dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap drafting sampai dengan pengumuman dalam lembaran negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu.
Sementara pengujian materil diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) huruf b UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa uji materil dengan materi muatan ayat, pasal dan atau bagian UUD RI 1945 dapat diminta untuk dinyataan tidak mempunyai kekuasaan merugikan secara hukum.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/helmichandrasy-dosen-fakultas-hukumuniversitasbunghatta.jpg)

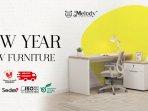







:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/peti-dhamasraya.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/Kondisi-cuaca-cerah.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/emas-terbaru.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/Wakil-Wali-Kota-Padang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/padang/foto/bank/originals/Kondisi-arus-lalu-lintas.jpg)